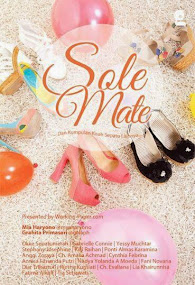“Kamu tahu
sebutan anak logam?”
Kamu mengerutkan
kening. Tentu saja, kamu yang lahir dan besar di Jakarta tidak tahu apa itu
anak logam. Kamu hidup di antara kemacetan jalan Sudirman, ujung Monas, asap knalpot
dari angkot-angkot dengan sopir yang merasa jelmaan dari pembalap F1, sampai
mal-mal besar yang bisa membuatmu tersesat di dalamnya.
“Jadi,
kalau kamu naik kapal laut dari Banyuwangi menuju Denpasar, kamu akan ketemu
sama anak-anak yang berenang di dekat kapal.”
“Berenang? Di
dekat kapal? Nggak ditabrak sama kapalnya?”
Kadang, kepolosan dan caramu bercanda membuat saya tidak bisa
membedakan keduanya. “Nggaklah. Biasanya kapalnya belum jalan, atau baru jalan, jadi mereka hati-hati. Mereka nunggu penumpang kapal yang mau
ngelemparin uang receh ke laut—uang logam. Kalau kamu lempar uang logam seratus
rupiah, mereka akan berebut ngambilnya.”
“Tapi, kan,
uangnya bakal tenggelam, gimana mereka ngambilnya?”
“Ya, mereka
berenang, menyelam. Siapa cepat dia dapat. Kalau salah satu dari mereka
berhasil dapat uangnya, mereka akan muncul ke permukaan dan mengangkat uangnya
tinggi-tinggi, sambil senyum lebar ke penumpang yang ngelihatin mereka dari dek.”
Keningmu makin
berkerut, membuat alis melengkungmu membetuk garis nyaris sejajar. “Menyelam cuma
buat duit seratus perak?”
“Dulu, sih,
seratus perak itu banyak. Berapa tahun yang lalu, ya? Hm—sekitar lima belas
tahun lalu mungkin. Waktu itu aku masih awal-awal SD. Sekarang, aku malah nggak tahu apa
anak-anak logam itu masih ada atau nggak.”
Kamu
mendengus, tapi bibirmu menyunggingkan senyum. Senyum tipis yang tidak pernah
tidak saya suka. “Anak logam itu seru, ya?”
Saya mengangguk. “Kamu tahu
bagian paling serunya?”
Kamu melebarkan
matamu. Mata yang bulat dengan warna kecokelatan. Kamu menggeleng.
“Anak-anak
logam itu menyelam tanpa memakai alat bantu apa pun. Mereka bahkan nggak pakai
kacamata renang. Jadi, kamu bisa bayangin gimana mereka harus membuka mata dan
menahan perih karena air laut yang asin dan gimana mereka harus kuat menahan
napas sampai uang logamnya ketemu. Sebelum uang logamnya jatuh makin dalam ke
dasar laut.”
Bibirmu kini
membuka, membentuk huruf O yang besar. “Gila. Nahan napas demi ngambil uang
logam doang? Tapi, buka mata di dalam air laut juga menyakitkan, sih. Itu pasti perih
banget.”
“Iya,
anak-anak logam kebanyakan matanya merah. Tapi, napas mereka panjang-panjang,
jangan salah. Pada bagus kalau ngaji.”
“Kamu
pernah jadi anak logam?”
“Aku memang besar di daerah yang dekat laut. Tapi, menyelam,
menyakiti diri sendiri untuk sesuatu yang hanya bisa kita nikmati sesaat? Duit seratus
perak yang kalau dikumpulin cuma bisa buat beli Chiki atau kelereng?” Saya
menggeleng. “Nggak pernah. Aku cuma pernah jadi anak pantai yang kerjanya
ngumpulin kerang. Itu juga akhirnya dibuang sama Ibu, dibilang sampah.”
Kamu tertawa
kecil. Tawa yang jarang sekali saya dengar terlalu berisik, lebih sering hanya
senyum lebar tanpa suara.
Saya mungkin
tidak pernah jadi anak logam. Tidak pernah berenang di laut, di bawah terik
matahari yang membuat kulit saya hitam legam. Tapi, saya tahu bagaimana rasanya
menyelam sampai ke dasar, menahan perih di mata saya, dan menahan napas yang membuat saya sesak,
demi sesuatu yang—saya tahu—tidak akan pernah bisa saya miliki selamanya.
Kamu.
Banyuwangi,
24 Oktober 2014
24 Oktober 2014
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO