“Apa ini?!”
Mataku mulai buram, segalanya terlihat kabur. Pening. Kucoba menutup mataku, sekuat mungkin. Berusaha mengalihkan semua yg sempat terlihat, berharap semua hanya ilusi. Naas, garis garis merah itu malah muncul di pikiranku. Tidak dimataku, tapi di otakku!
Tuhan. Aku berdosa.
Kuraih gagang telepon di sudut ruang tengahku. Kutekan tombol tombolnya dengan jari lentikku yang bergetar. Kugigit bibirku gelisah. Sambil jari telunjuk dan tengahku memilin kabel telepon. Nada sambung pertama. Aku diam. Dengan gugup aku mengeja setiap huruf yang akan kujadikan sebuah pilihan kata. Nada sambung kedua. Kalimat! Jadilah sebuah kalimat! Pintaku pada sang otak! Nada sambung ketiga. Hening. Garis garis merah itu kembali terbayang jelas di pikiranku.
“Hei...” suara riang menyapa disebrang sana.
“Oh... heii...” aku menghela nafas. Apa yang harus kukatakan? Bisakah dia menerimanya? Akankah dia mau berbesar hati dan mengakui semuanya? Bingung.
“Kok diem?” dia kembali mengusik. “Masih pusing? Minum obatnya lagi.”
“Tenangkan dirimu! Jangan berlagak kayak anak kecil.” dia mulai membentak. “Kamu pikir aku nggak bingung? Nggak takut?” aku diam.
Bangunan kecil berbentuk rumah itu berkesan tua. Catnya serba putih. Aku tak tau jelas apa nama tempat itu. Papan namanya terlihat buram di mataku. Yang aku tau, tempat ini disebut laboratorium. Memang apa saja yang diuji disini?! Aku tak sempat memikirkannya lebih jauh, seseorang memanggil namaku, Putri Soraya. Aku berdiri, menghampiri wanita berbaju putih, semuanya berbaju putih disini, aku mulai mual.
Aku melirik sepasang mata yang menatapku. Dia diam, tegang. Haruskah aku melakukan ini semua? Di dalam sini? Tuhan, aku takut, takut sekali.
Wanita berbaju putih itu menyodorkan sebuah tabung. Pasti tabung ini punya istilah sendiri dalam dunia kedokteran, atau fisika, kimia? Ah...aku tak sempat mengingatnya. Yang aku tau, aku harus mengisinya dengan tetes tetes air dari tubuhku. Aku takut. Garis garis merah itu kembali muncul di benakku. Aku mulai membenci warna merah!
“Aku takut.” Kucoba mencari ketenangan dalam matanya. Dalam genggam tangannya. Dia tersenyum. Tampan. Meski tak sepatah kata yang dilontarkan, tapi aku sedikit tenang. Dia akan ada disampingku. Pasti.
Lima menit. Tak ada yang berarti
Sepuluh menit. Haruskah lebih lama lagi?
Lima belas menit berlalu. Aku mulai tersiksa, gelisah.
Dua menit kemudian, wanita berbaju putih yang sama menoleh ke arahku. Kembali memanggil namaku diiringi senyumnya yang mulai menua. Senyumnya terlalu tulus, terlalu manusiawi dan itu membuatku semakin ketakutan. Segera, pilihan katanya tepat menusuk ulu hatiku.
Aku tak tau harus menangis atau apa. Lidahku kelu. Bibirku beku, kaku.
Tuhan. Aku berdosa.
Langkahku gontai, tapi pasti. Pria disampingku tetap berdiri tegak. Tidak taukah dia gejolak dalam hatiku? Tak taukah dia betapa aku ingin dia menyelamatkanku?
Garis garis merah itu lagi lagi muncul di benakku. Positif. Ya, positif!
Ucapan selamat dari wanita berbaju putih itu juga terngiang di telingaku. “Selamat ya... anda dan suami anda akan jadi orang tua. Orang tua yang bahagia.”
Aku? Suamiku? Orang tua? Jangankan sebuah maskawin, dia bahkan tidak melamarku. Lalu aku harus jadi orang tua macam apa?! Aku tidak ingin melahirkannya. Aku tidak ingin semua impian dan masa depanku hancur hanya karna aku salah memilih untuk menjadi orang tua. Bukan mahasiswa, bukan pegawai bank, penulis, designer, bahkan wanita karir. Aku ingin bahagia. Aku masih muda, cantik, kata orang aku pintar. Aku harus tetap seperti itu. Pilihan yang menungguku masih banyak. Aku harus kuat, tega. Kejam.
Bibirku yang tipis kembali berbohong. Memuluskan niatku untuk membuang hasil perbuatan laknatku yang tak berdosa. Aku berbohong, Tuhan. Ini salah, benar benar salah. Tapi apalagi pilihanku?! Studyku masih menanti. Karier, teman temanku, tak terbayang apa jadinya jika aku kehilangan itu semua.
... ... ... ... ...
“Jangan kayak anak kecil. Jangan mewek.” Dia lagi lagi membentak. “Kita udah sampe sini, kamu ga mungkin mundur kan?!” dan aku hanya mengangguk lemah sebelum kembali kuangkat daguku.
Tuhan. Aku berdosa.
Hanya dalam hitungan menit, aku merasa lambungku terkoyak. Bukan, bukan lambung, itu rahim! Mataku panas. Aku ingin menghentikan semuanya. Aku ingin teriak, menangis. Aku ingin berkata, “Jangan renggut dia, dia tidak bersalah, aku menginginkannya.” Aku tau rahimku mulai terluka. aku menginginkannya, meskipun tanpa maskawin darinya, aku akan melahirkannya. Aku akan merawatnya.
Terlambat.
Gumpalan darah memenuhi sebuah baskom kecil. Anakku! Itu anakku!
Tuhan. Aku berdosa.
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

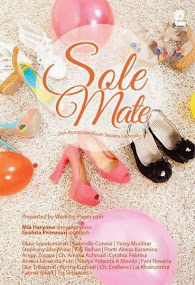




April 23, 2012 at 12:29 PM
seringkali,kita bersikap egois untuk menyelamatkan diri kita sendiri...
April 24, 2012 at 10:09 AM
kadang jga egoisme itu diartikan sebagai pilihan, menyelamatkan yang lain atau kita dulu.. hehe
makasih udh komen disini mbak cantik.. :)